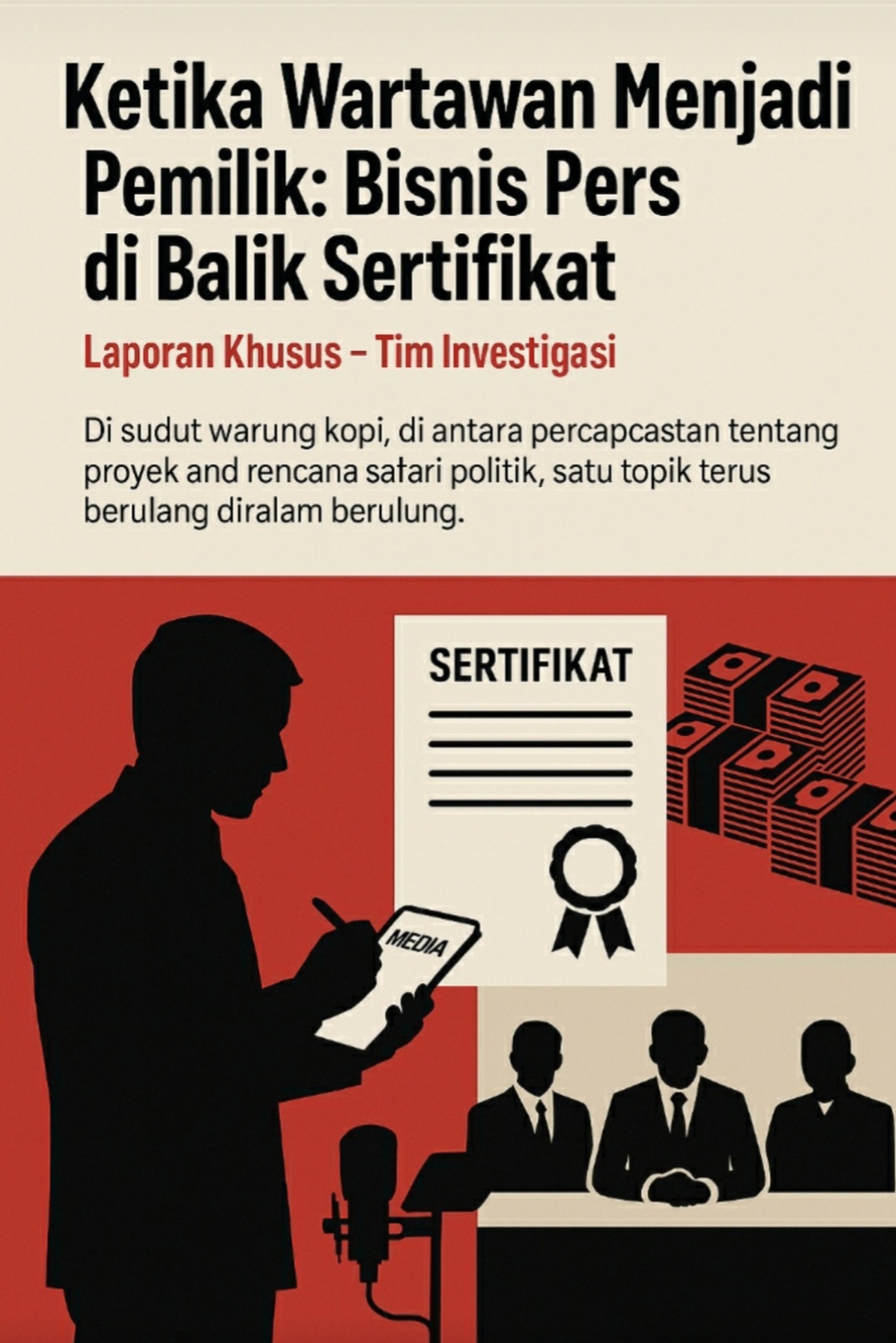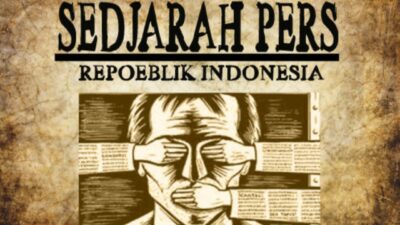Laporan Khusus: Intelektualitas Dikesampingkan Demi Rente
Pelita Aceh.co.id | BANDA ACEH — Di sudut warung kopi, di antara percakapan tentang tender proyek dan rencana safari politik, satu topik terus berulang dalam bisikan: tentang para wartawan yang kini punya media sendiri. Tak lagi seperti biasa ‘Ada dimana mana, Dengan dalihan tak tahu mau kemana’. Tak lagi sekadar peliput, mereka telah menjadi pemilik. Tak lagi bertugas mengawasi kekuasaan, mereka kini duduk berdampingan dengan para pemilik anggaran.
Fenomena ini tak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari celah antara idealisme profesi dan kenyataan ekonomi. Wartawan yang telah bertahun-tahun bekerja di media massa, bahkan yang bersertifikat resmi dari Dewan Pers, mulai berbondong-bondong mendirikan perusahaan pers sendiri. Sebagian melakukannya secara terang-terangan. Sebagian lagi diam-diam—menggunakan nama istri, anak, atau kerabat lain sebagai representasi legal dalam akta notaris.
Motivasinya sederhana namun menggoda: anggaran publikasi dan promosi di dinas-dinas pemerintahan yang terus membesar setiap tahun. Nilainya mencapai miliaran rupiah, tersebar dalam bentuk iklan layanan, advertorial, dan kerja sama media. Bagi mereka yang sudah punya jaringan dengan pejabat, akses terhadap dana ini tinggal satu lobi singkat.
“Cukup angkat telepon, sebut nama medianya—meskipun baru seumur jagung—lalu dikucurkan dana. Semua karena kedekatan lama,” ungkap seorang sumber dari organisasi pers, yang meminta identitas dan institusinya dirahasiakan.
Media ‘Keluarga’ dan Redaksi Semu
Tim Investigasi menemukan bahwa banyak perusahaan pers ini dibentuk dengan pola serupa: akta notaris resmi, situs web beralamat domain murah, dan struktur redaksi seadanya. Direktur biasanya istri, pemimpin redaksi anak atau sepupu. Reporter? Kadang tak ada sama sekali. Kadang hanya satu orang yang merangkap semua fungsi.
“Media saya ada semua syaratnya. Redaksi juga lengkap, meskipun sebenarnya saya yang kerjakan semua,” aku seorang pemilik media yang juga mantan wartawan harian lokal, saat ditemui di sebuah warung kopi kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh.
Situs-situs web media ini umumnya menggunakan template standar, dengan konten minim, dan berita yang mayoritas merupakan hasil salin-tempel dari rilis instansi. Tak ada kerja jurnalistik mendalam, danjuga liputan investigatif. Namun, cukup untuk mencetak screen capture dan melampirkannya dalam proposal kerja sama.
Nama-nama yang tercantum dalam redaksi sering kali bahkan tidak mengetahui bahwa identitas mereka digunakan. Beberapa lainnya sekadar “pinjam nama” agar terlihat profesional di atas kertas. Dalam banyak kasus, tidak ada rapat redaksi, tidak ada proses editing, dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban editorial.
Jaringan yang Dipakai Ulang
Panjang pengalaman mereka di dunia jurnalistik, terutama bagi yang telah puluhan tahun bekerja sebagai wartawan, menjadikan mereka punya modal sosial yang sangat kuat. Kenalan di lingkungan pejabat dinas, legislatif, hingga TNI dan Polri, kini bukan lagi narasumber yang dijaga jarak. Tapi mitra, bahkan dalam beberapa kasus, bagian dari jaringan bisnis media itu sendiri.
“Bukan rahasia lagi, kalau wartawan senior itu bisa minta langsung ke kepala dinas. Kadang tak pakai proposal pun tetap dikasih anggaran,” kata seorang staf keuangan di salah satu instansi pemerintah di Banda Aceh.
Simbol-simbol profesi digunakan untuk membuka pintu-pintu itu. Kartu pers, logo media, bahkan seragam liputan, semua dijadikan alat pendekatan. Tapi di baliknya, yang dijalankan adalah agenda ekonomi pribadi.
Salah satu pola paling kentara dalam praktik ini adalah kecenderungan media baru—yang dikelola wartawan bersertifikat—untuk mengejar iklan pariwara dan ucapan selamat dari pejabat atau institusi tertentu. Momen-momen seperti HUT media, HUT RI, hari besar nasional, hingga pelantikan pejabat sering dijadikan momentum berburu ucapan selamat berbayar.
“Biasanya kami kirim surat ke dinas-dinas, tawarkan space ucapan selamat. Tarikannya dari Rp500 ribu sampai Rp3 juta per tayang, tergantung siapa yang tanda tangan,” ungkap seorang pemilik media online di wilayah Banda Aceh.
Iklan pariwara pun tak kalah strategis. Beberapa media bahkan sengaja menerbitkan rubrik-rubrik semi-editorial untuk menampung advertorial dinas, namun tetap dikemas seolah berita. Tidak ada penandaan “iklan” atau “advertorial”. Semua mengalir dalam bentuk liputan kegiatan dengan narasi yang dibersihkan dari kritik.
Dalam sistem ini, sertifikat kompetensi wartawan bukan hanya alat validasi profesional, tapi menjadi senjata negosiasi. Wartawan yang telah bersertifikat dianggap sah mewakili institusi pers, dan karenanya lebih dipercaya oleh dinas-dinas, meskipun medianya sendiri tak punya oplah, tidak update berkala, dan tak pernah meliput di lapangan.
Kolaborator Baru: Pejabat, ASN, Aktivis, dan Polhut
Yang mengejutkan, tidak semua pemilik media berasal dari latar belakang jurnalis. Kini, siapa saja bisa memiliki media sendiri. Tim Investigasi menemukan keterlibatan pensiunan pejabat, ASN aktif, kontraktor lokal, bahkan politisi yang menciptakan media sebagai corong politik pribadinya.
“Kalau punya media, kita bisa bantu narasi dinas. Lagipula, kalau tak diambil orang kita, pasti diambil orang lain,” ujar seorang polisi hutan di wilayah yang dekat dengan ibukota Aceh. Dia mengaku turut serta dalam pendirian sebuah media daring.
Aktivis LSM pun turut masuk dalam gelanggang ini. Mereka yang dulu bersuara lantang di forum-forum advokasi kini membentuk media sendiri—bukan untuk memperkuat kontrol sosial, tapi untuk ikut mengakses dana publikasi pemerintah.
“Kadang LSM-nya tetap jalan, tapi media yang mereka buat justru jadi saluran utama cari anggaran ke dinas-dinas. Kirim proposal, buat liputan kegiatan, lalu dapat paket iklan,” kata seorang narasumber dari Langsa yang pernah menjadi mitra salah satu LSM.
Dengan pengalaman lobi dan jejaring donor, para aktivis ini tak kesulitan menyusun narasi media yang tampak profesional. Namun kontennya sebagian besar tetap berorientasi pada kepentingan pemberi dana. Beberapa di antaranya bahkan menanggalkan fungsi advokasi dan lebih fokus pada monetisasi media sebagai bisnis.
Panggung Ilusi, Bahaya Nyata
Kondisi ini menciptakan ilusi di mata publik: media tampak menjamur, jurnalisme seolah hidup, tapi sebenarnya yang tumbuh adalah bayang-bayangnya. Banyak berita yang hanya tayang karena dibayar. Banyak media yang hanya aktif ketika ada proyek. Selebihnya, sunyi.
Etika jurnalistik yang dulu menjadi kitab suci redaksi, kini disingkirkan ke pinggir ruangan. Dibuka hanya saat seminar, dikutip bila mengajukan proposal, tapi jarang benar-benar dijalankan.
“Ini bukan sekadar persoalan moral. Ini sudah masuk ke wilayah manipulasi informasi publik. Masyarakat tidak tahu lagi mana berita yang sungguh-sungguh, mana yang hanya pesanan,” ujar sumber investigasi yang selama ini aktif dalam pemantauan media di Lhokseumawe.
Dewan Pers dan PWI Pusat Belum Merespons
Hingga laporan ini ditayangkan, redaksi media ini belum berhasil menghubungi pihak Dewan Pers maupun Pengurus PWI Pusat untuk dimintai tanggapan. Hal ini disebabkan redaksi belum memperoleh kontak person yang layak dan dapat memberikan konfirmasi resmi terkait fenomena ini.
Sementara itu, praktik-praktik ini terus berlangsung secara terbuka di berbagai kabupaten/kota. Dari proposal ke proposal, dari lobi ke lobi, media tak lagi menjadi anjing penjaga demokrasi. Ia telah menjadi makelar dalam jaringan relasi kekuasaan asal bapak senang (ABS) seraya mengacungkan jempol BERES.
Dan jika semua ini terus dibiarkan, akan tiba waktunya ketika publik tak bisa lagi membedakan mana yang berkarakter jurnalis, mana yang hanya berperinsip pebisnis yang notabene nya menyamar. Saat itu, kehormatan profesi ini akan kehilangan makna sepenuhnya.
(Tim Investigasi)
Dari Pejabat Basah ke Media Sampah: Jejak Busuk Wartawan Pencari Jatah
Jakarta — Reputasi seorang pria berinisial SO, mantan pejabat eselon yang pernah berpengaruh di salah satu instansi pengelola anggaran publikasi, kini berada di ujung tanduk dalam pandangan sebagian insan pers.
Pasca pensiun, SO mencoba peruntungan baru dengan mendirikan sebuah media daring yang ia kelola dari rumahnya sendiri. Namun, langkah itu tak serta-merta menjadikannya pelopor kebebasan pers. Justru sebaliknya, banyak pihak menilai media tersebut hadir sebagai saluran jurnalisme pelampiasan—penuh ancaman, kritik sepihak, dan nuansa pribadi yang kental.
“Bukan sekadar media, tapi cermin kekecewaan yang dibungkus berita,” ujar seorang pemilik media lokal, Kamis, 10 April 2025.
Saat masih aktif sebagai pejabat, SO dikenal sebagai figur yang menguasai distribusi anggaran iklan dan kerja sama publikasi bernilai besar. Akses ke program tersebut tak mudah, dan banyak yang menyebutnya sarat syarat tak tertulis. Kini, setelah tak lagi punya kewenangan formal, ia mencoba menghidupkan kembali pola-pola itu lewat media pribadi.
Dengan akta notaris dan stempel redaksi, SO menjadi pemimpin redaksi tunggal. Ia menulis sendiri, menyunting sendiri, bahkan mencetak kartu pers dan menyebarkan konten sendiri. Namun, media yang ia bangun justru mendapat sorotan dari sejumlah jurnalis profesional karena dianggap menyebarkan narasi yang sarat bias dan tidak melalui standar kerja jurnalistik yang sehat.
Ketika beberapa media lain menolak bekerja sama dengan model transaksional, tudingan miring justru datang dari arah SO. Ia menyebut mereka sebagai “abal-abal”, “partisan”, hingga “tidak layak baca”. Namun label itu dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk serangan balik karena kepentingan pribadi tidak dipenuhi.
“Media ini menulis bukan untuk publik, tapi untuk tekanan,” kata seorang wartawan muda yang merasa pernah menjadi target pemberitaannya.
Pemberitaan yang diterbitkan media SO sering kali tak melalui proses konfirmasi yang memadai. Bahkan pernah memuat klaim sepihak tentang pergantian pimpinan partai politik besar di daerah. Setelah diprotes keras, berita itu dihapus tanpa klarifikasi ataupun permintaan maaf. Hal ini memperkuat kesan bahwa media tersebut dijalankan dengan pendekatan yang mengabaikan etika dan kaidah dasar jurnalistik.
Lebih dari itu, beberapa media yang kerap mengutip atau menyebarkan narasi dari SO juga mulai dipertanyakan. Mereka diduga menjadi bagian dari jaringan tekanan terhadap media lain, terutama yang tak memberi ruang atau anggaran. Ketika gagal ‘masuk’, maka narasi bergeser: dari kerja sama menjadi tudingan KKN.
Tak berhenti di situ, kelompok ini kini mulai masuk ke bisnis promosi visual, seperti baliho dan spanduk. Proyek-proyek besar, termasuk kegiatan berskala nasional seperti PON Aceh, menjadi ladang baru. Sebagian besar media mereka bungkam soal isu-isu negatif, bukan karena tak ada masalah, tapi karena sebagian anggaran promosi sudah mengalir ke mereka.
“Kalau mereka tidak dapat jatah, suara mereka akan berubah bising. Tapi begitu kenyang, kritik hilang,” ujar seorang jurnalis senior.
Fenomena ini menunjukkan luka lama dunia pers yang belum kunjung sembuh. Ketika ruang redaksi dikuasai oleh eks pejabat kecewa dan jurnalis uzur yang masih lapar kuasa, maka yang lahir bukan berita, tapi sampah informasi yang dibungkus sebagai kebenaran.
Dan dalam situasi itu, publik kembali menjadi korban. Mereka dijejali narasi-narasi penuh bias, opini tanpa dasar, dan laporan yang lebih mirip pamflet tekanan daripada produk jurnalistik.
Tak heran jika belakangan, sejumlah jurnalis menjulukinya dengan nama baru: Spesialis Olah—bukan dalam arti investigatif, melainkan mengolah data mentah menjadi narasi penuh dendam.
(EI)
Disclaimer: Tulisan ini adalah karya naratif berbasis isu aktual dan fenomena etis dalam dunia jurnalistik. Segala kemiripan dengan individu atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan semata.